Pandemi Covid-19 adalah masalah yang berdampak pada setiap elemen masyarakat, mulai dari adanya aturan baru yang mengadaptasi situasi, perubahan situasi ekonomi, hingga terujinya rasa kemanusiaan untuk saling membantu. Berbagai inisiatif dalam merespons pandemi dilakukan, baik itu oleh negara, sektor swasta, hingga masyarakat akar rumput. Namun, bagaimana dan apa peran masing-masing sektor masyarakat ini untuk memastikan akuntabilitas dalam kebijakan, inisiasi, gerakan, maupun program yang merespons pandemi?
Bung Hatta Anti-Corruption Award mengundang Heru Pambudi (Dirjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI, Peraih BHACA 2017), Alissa Wahid (Koordinator Jaringan Gusdurian), dan Karaniya Dharmasaputra (Presiden Direktur OVO, Peraih BHACA 2003) dalam diskusi berjudul, “Akuntabilitas Penanganan Pandemi Covid-19: Peran Negara dan Masyarakat”
Merespons pandemi Covid-19, Jaringan Gusdurian yang dikoordinasi oleh Alissa Wahid menargetkan bantuan untuk pekerja sektor informal dengan menggerakkan anggota jaringan yang mampu mendistribusikan bantuan hingga menyentuh akar rumput. Untuk memastikan akuntabilitas distribusi bantuan sosial, Jaringan Gusdurian membentuk lembaga formal bernama Yayasan Gusdurian Peduli dan menerapkan mekanisme audit serta pelaporan pengumpulan dan penggunaan keuangan masing-masing program secara terbuka. Jaringan Gusdurian juga berkomitmen untuk menekan biaya operasional dengan memberdayakan pekerja informal (seperti ojek pangkalan untuk mendistribusikan bantuan). Alissa Wahid menekankan pentingnya akuntabilitas demi membangun kredibilitas suatu gerakan solidaritas.
Berbicara mewakili elemen pemerintah, Heru Pambudi menjelaskan berbagai kebijakan pemerintah merespons pandemi, seperti pembebasan fiskal dan cukai untuk beberapa barang demi memastikan ketersediaan alat kesehatan dan bahan pangan, serta mempermudah birokrasi impor untuk instansi seperti rumah sakit atau kampus. Demi memastikan akuntabilitas dan transparansi, Dirjen Bea dan Cukai mengandalkan otomasi dan fasilitas trace and track yang juga dapat dipantau oleh masyarakat. Heru Pambudi melihat bahwa situasi pandemi memberikan peluang untuk membentuk kebiasaan baru seperti mengejar efisiensi tata kelola, penghematan anggaran, dan transparansi birokrasi.
Tidak hanya masyarakat akar rumput saja yang ingin turut membantu, namun juga sektor swasta. Karaniya Dharmasaputra membagikan pengalaman dan pelajaran dari Ovo, Tokopedia, dan Grab melalui pemanfaatan teknologi digital bekerja sama dengan organisasi kemasyarakatan untuk menghimpun dana masyarakat serta mendistribusikan bantuan dengan tetap meminimalkan kontak manusia. Melalui kacamata sektor swasta, Karaniya menggarisbawahi pasal-pasal karet yang meski memiliki semangat antikorupsi namun dapat menjadi alat korupsi baru dan melemahkan peran sektor swasta. Menurut Karaniya, negara dan demokrasi akan kuat jika tiga elemen (negara, masyarakat, dan swasta) dapat bersinergi dengan baik. Situasi baru yang dibentuk oleh pandemi ini memaksa kita untuk melihat dan membuat budaya baru dan sistem baru.
Rekaman Diskusi Online BHACA bertajuk “Akuntabilitas Penanganan Pandemi Covid-19: Peran Negara dan Masyarakat” yang diselenggarakan pada 7 Mei 2020 dapat disaksikan di Facebook Bung Hatta Award dan YouTube Bung Hatta Award.








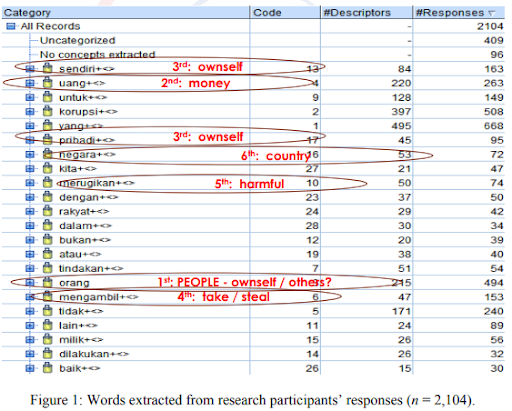
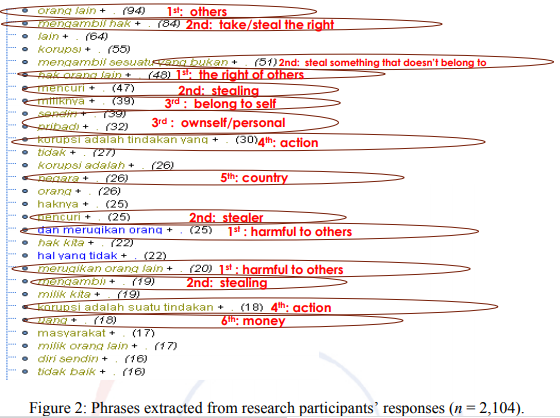





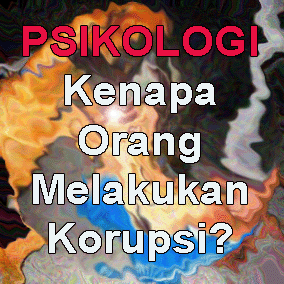

Recent Comments