Tantangan di tengah pandemi covid-19 tidak hanya persoalan kesehatan tetapi juga masalah pemberantasan korupsi. Tertangkapnya Menteri Sosial Juliari Batubara dan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo serta sejumlah politisi yang terseret dalam pusaran beberapa kasus korupsi merupakan sesuatu hal yang sangat memprihatinkan. Di satu sisi, terungkapnya kasus-kasus ini mengonfirmasi indikasi bahwa banyak kebijakan negara yang dibancak dan banyak pula pejabat pengelolanya yang tidak berintegritas. Di sisi lain, ini merupakan tantangan bagi aparat penegak hukum untuk mengusut semua yang terkait tanpa pandang bulu sampai tuntas.
Pada 22 Februari 2020 lalu, BHACA menggelar diskusi online dengan tajuk “Pemberantasan Korupsi Kala Pandemi,” menghadirkan dua narasumber utama yaitu Dewi Anggraeni NP (Peneliti ICW) dan Laode M Syarif (Direktur Eksektuf Kemitraan, Wakil Ketua KPK 2015 – 2019). Diskusi ini sekaligus memperingati Hari Keadilan Sosial yang bertujuan untuk mempromosikan keadilan sosial.
Dalam paparannya, LMS menyampaikan berdasarkan pengalaman empirik, dana untuk bantuan sosial atau penanganan bencana kerapkali dikorupsi. “Setiap dana besar untuk bantuan sosial atau subsidi sering dikorupsi.” LMS mencontohkan anggaran Tsunami Aceh dimana uang Rp5 triliun tidak jelas juntrungannya. Begitupula, dana flu burung & pengadaan alat kesehatan sekitar Rp12,33 miliar raib. Kasus BLBI yang dikorupsi Rp138 triliun hingga Bank Century nilai korupsi mencapai 6,742 triliun. Anggaran penanganan Tsunami Jawa Barat dan Gempa Lombok juga dikorupsi hingga anggaran Gempa Likuifaksi Palu dikorupsi Rp 2,9 miliar,” paparnya.
Mengapa korupsi terhadap dana-dana kemanusiaan dikorupsi? Menurut LMS penyebabnya adalah dasar hukum yang longgar dan kurangnya pengawasan. Korupsi dana darurat sebelum bansos memang tidak mengenal dasar hukum yang khusus dan mekanismenya normal. Dalam konteks korupsi bansos di tengah pandemi, problemnya terletak pada UU yang membuka ruang korupsi. Sebagaimana diketahii bahwa dalam UU No 2 Tahun 2020 khususnya Pasal 27 ayat (1), (2), dan (3) mengamanatkan penyesuaian, pergeseran, dan pengeluaran anggaran tanpa persetujuan DPR.
Problem lain ialah terletak padaa data orang miskin tidak lengkap, penunjukan langsung diperbolehkan, pengawasan lemah, pemanfaatan dana bansos untuk kepentingan politik. Oleh karena itu, menurutnya, ke depan harus segera dilakukan perbaikan data, memperkuat koordinasi, dan pengawasan harus ketat dan melekat. Selain itu, LMS menyarankan untuk diwaspadai dana insentif usaha, pembiayaan koorporasi,dan UMKM yang belum jelas realisasinya.
Dewi Anggraeni dari ICW memaparkan hal-hal yang dilakukan ICW untuk melihat korupsi di pandemi. Ia menjelaskan bansos ada banyak masalah dari hulu-hilir, dari pendataan, pengadaan, proses pengadaan, realisasi hingga distribusi sampai informasi anggaran. Berdasarkan pemantauan ICW terhadap distribusi bansos sepanjang Juni – Agustus 2020, distribusi bansos belum tepat sasaran dan penuh persoalan termasuk pungli dan politisasi. Dari survei distribusi bansos di Kupang, Bandung, dan DKI ditemukan permasalah-permasalah sebagai berikut:
- Pendataan penerima bansos penyandang disabilitas masih bermasalah dan tidak akurat (inclussion dan exclussion error)
- Adanya pemotongan bansos
- Penerimaan bansos tidak tepat waktu
- Informasi mengenai adanya bansos belum diketahui penyandang disabilitas, serta belum ramah disabilitas, lengkap, dan mudah dimengerti
- Informasi kanal pengaduan bansos belum banyak diketahui penyandang disabilitas
- Bentuk dan jumlah bansos yang diberikan belum sesuai dengan informasi yang diketahui, termasuk kualitas bansos yang tidak layak konsumsi.
Monitoring terhadap pengadaan barang dan jasa juga sarat problema mulai dari rencana pengadaan terlalu umum, uraian, spesifikasi, bentuk tidak terjelaskan secara detail dan sulit diakses. Identifikasi kebutuhan yang tidak berdasarkan kebutuhan lapangan. Terjadi jual beli penunjukan penyedia dan Surat Perintah Kerja (SPK) dari PPK. Sehingga penunjukan penyedia tidak sesuai ketentuan yaitu berpengalaman di pengadaan sejenis, dan juga penunjukan penyedia didasarkan suap atau konflik kepentingan. Potensi penyedia yang ditunjuk PPK, hanya mempunyai modal kemudian melakukan subcon pekerjaan utama kepada pihak lain. Melakukan pelunasan pembayaran padahal pekerjaan belum selesai. Ironisnya, korupsi juga menyasar bansos untuk penyandang disabilitas.
Masalah dalam PBJ, antara lain:
- Pengadaan alat kesehatan dan bantuan sosial belum transparan
- Perencanaan pengadaan (alat uji, alat pelindung diri, dll) tidak terinformasi dengan baik dan transparan, baik di RUP, LPSE, maupun website resmi Badan Publik. Bahkan terkait bansos, tidak ada informasinya sama sekali yang bisa dengan mudah diakses publik.
- Metode pengadaan tidak terinformasi dengan jelas sehingga tidak dapat dipantau oleh publik atau masyarakat. Meski ada Peraturan LKPP No 13 Tahun 2018 dan Surat Edaran LKPP Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengadaan Darurat, tetapi tidak serta merta informasi perencanaan dan pengadaannya minim informasi.
- Data-data dan informasi tidak valid/minim menyebabkan kebingungan atau keacuhan oleh publik, bahkan hingga menyebabkan kematian para tenaga medis.
- Distribusi alat material kesehatan dan bantuan sosial
- Informasi penerima dan jenis barang yang didistribusi tidak diinformasikan dengan baik.
- Anggaran belanja kesehatan dan bantuan sosial
- Hanya diinformasikan secara gelondongan. Terkait bantuan sosial sebagai salah satu upaya pemulihan ekonomi masyarakat
Bagaimana ke depan? Dewi merekomendasikan:
- Membuat perencanaan PBJ dan realisasinya secara transparan di SiRUP dan LPSE.
- Melibatkan publik dalam pengawasan secara maksimal sejak dari perencanaan (identifikasi kebutuhan) hingga realisasi pengadaan.
- Penanganan korupsi terkait pandemi Covid-19 patut dijadikan prioritas.
- APH menelusuri pihak/kementerian lain yang berpotensi terlibat atau mempunyai peluang penyelewengan pengadaan publik
Rekaman lengkap: https://www.youtube.com/watch?v=97REJzPxZ-4





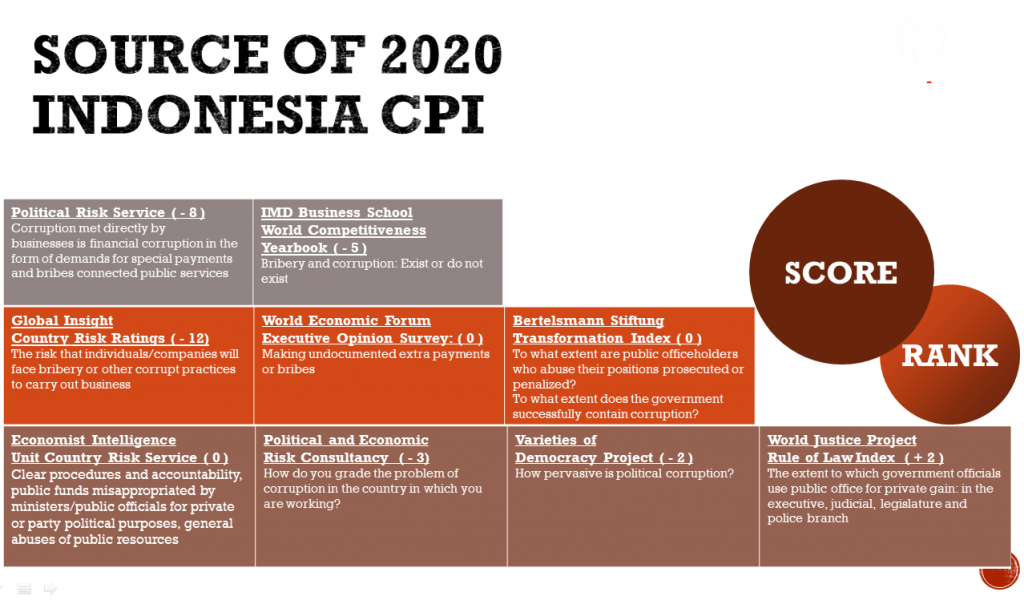
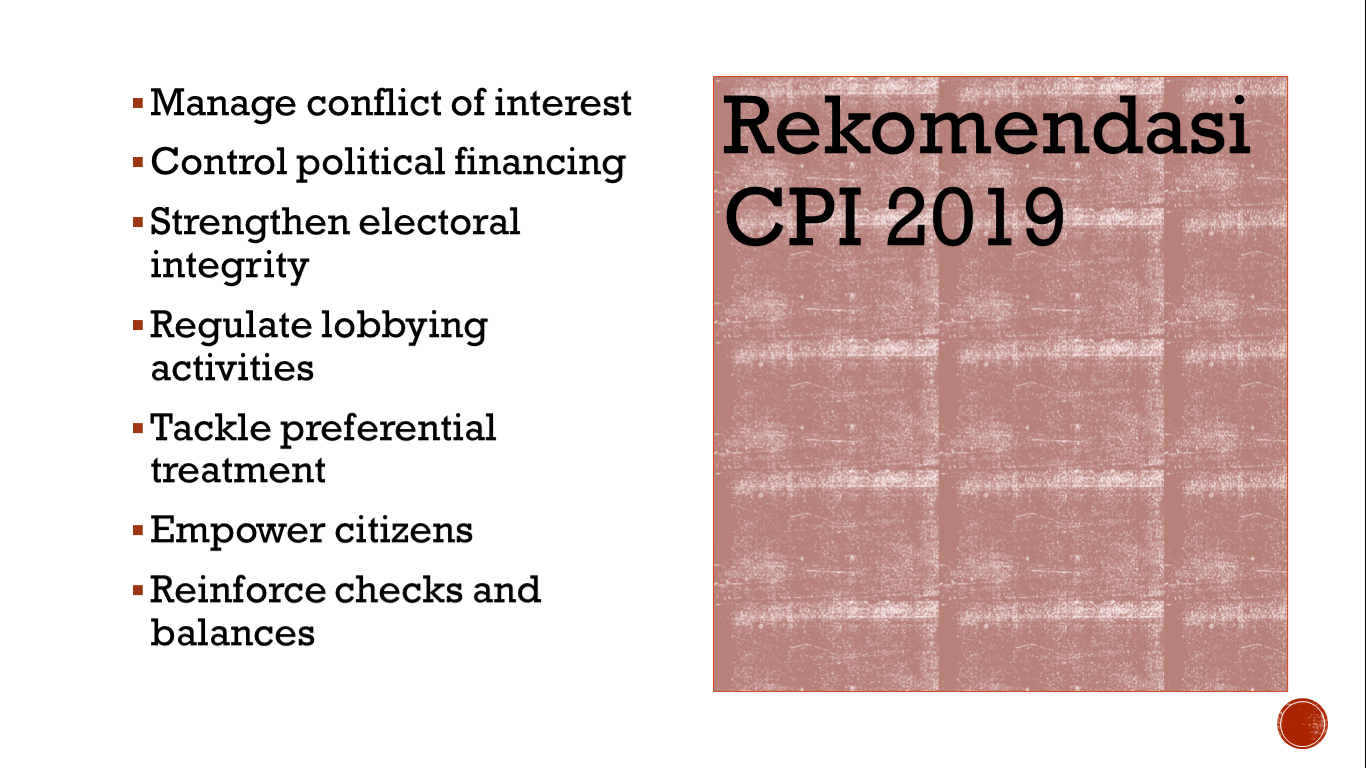
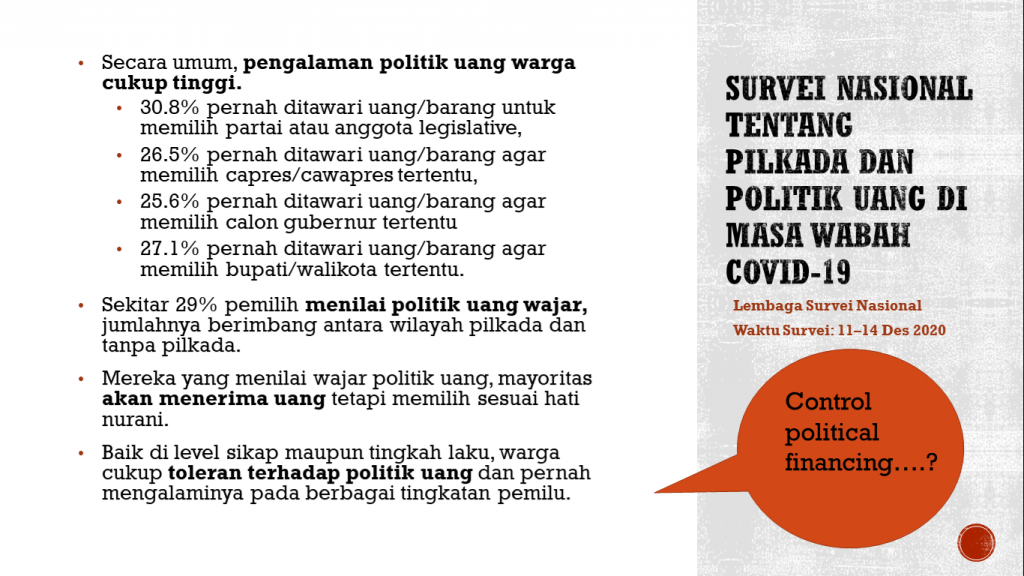



Recent Comments