Restorative justice dalam penyelesaian perkara korupsi meskipun tidak selalu menjadi pembahasan serius, wacana ini sering muncul dalam perdebatan penanganan perkara korupsi. Satu sisi, aparat penegak hukum yang menangani kasus korupsi jumlah kecil dalam beberapa kasus menginginkan proses penyelesaiannya lebih efisien. Karena dipandang kerugian negara yang mungkin akan kembali pada negara kecil, dibandingkan biaya penanganan perkara. Di sisi lain, kerangka hukum dan mekanisme penyelesaian dengan restorative justice belum tersedia.
Paradigma pemidanaan modern yang menghendaki pemulihan dibanding sekadar penghukuman terhadap pelaku dalam penyelesaian tindak pidana korupsi nampak mengalami sejumlah kesulitan. Policy brief ini menemukan sejumlah tantangan paradigmatik dan praktik secara khusus di ranah penuntutan yakni kesulitan menentukan subyek korban, kesulitan menyelenggarakan proses perdamaian/pemulihan, tidak ada ukuran yang pasti terkait besar kecilnya korupsi, sulit membuat sederhana persidangan tindak pidana korupsi, potensi tindak pidana baru dalam proses penyelesaian, hingga pertentangan pendekatan restorative justice dengan ketentuan pengembalian kerugian negara tidak menghapuskan dipidanannya pelaku serta problema dari sisi sosiokultural. Meskipun terdapat mekanisme/pendekatan di luar pendekatan restorative justice seperti linency policy, quasi seponering, dan/atau penerapan asas oportunitas, pilihan-pilihan tersebut belum tepat untuk penyelesaian kasus korupsi.
Unduh policy brief – restorative justice


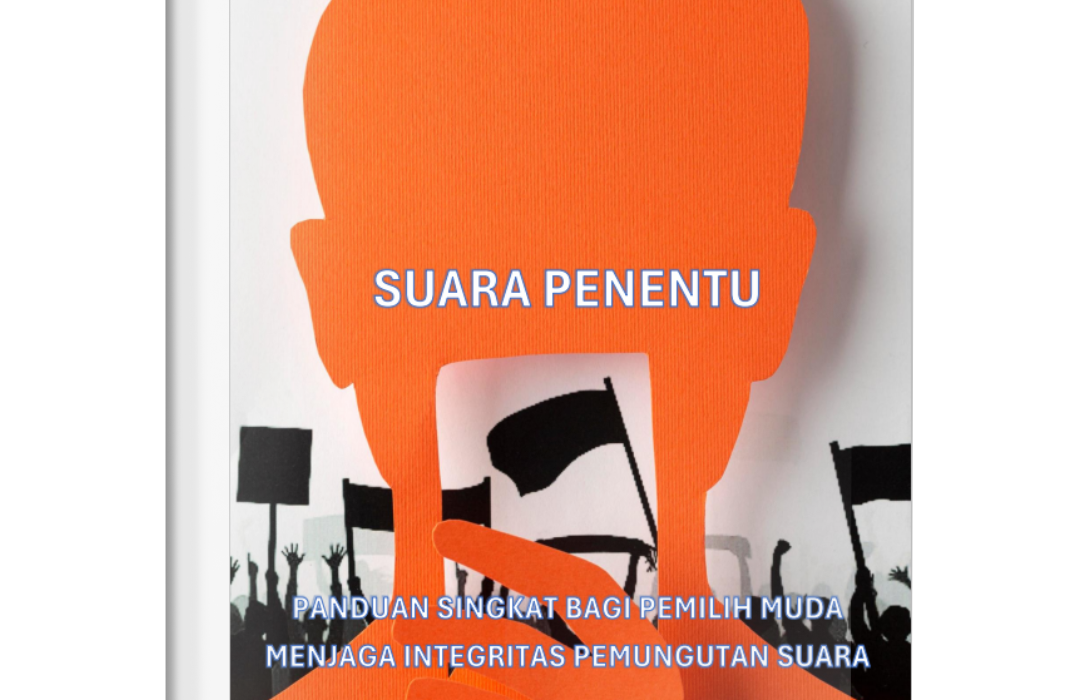
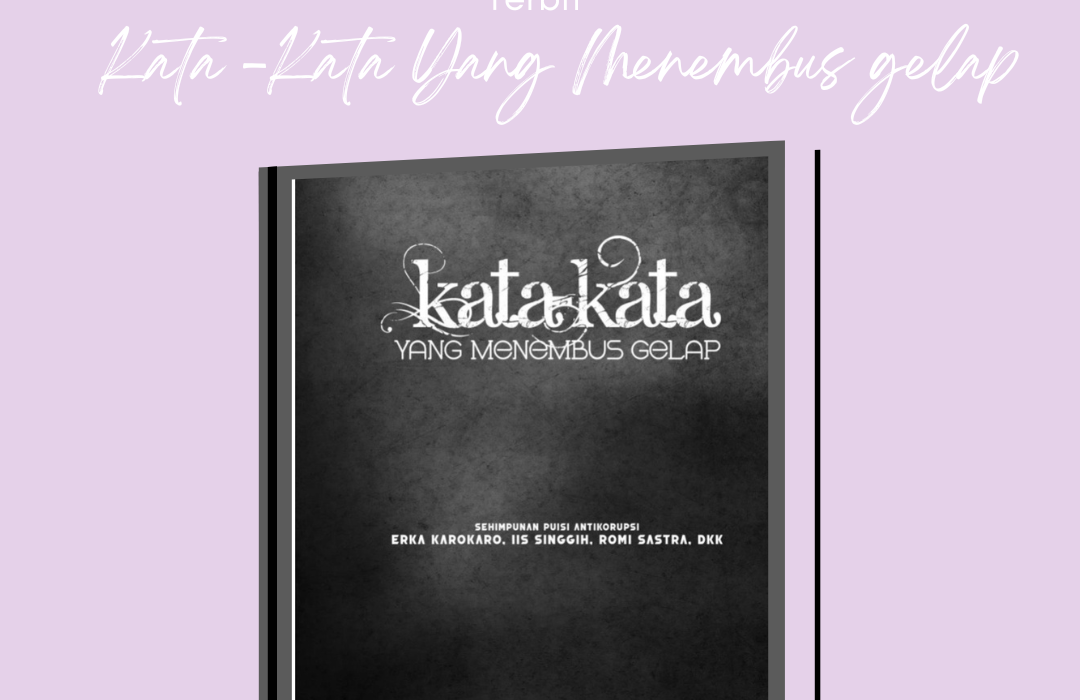
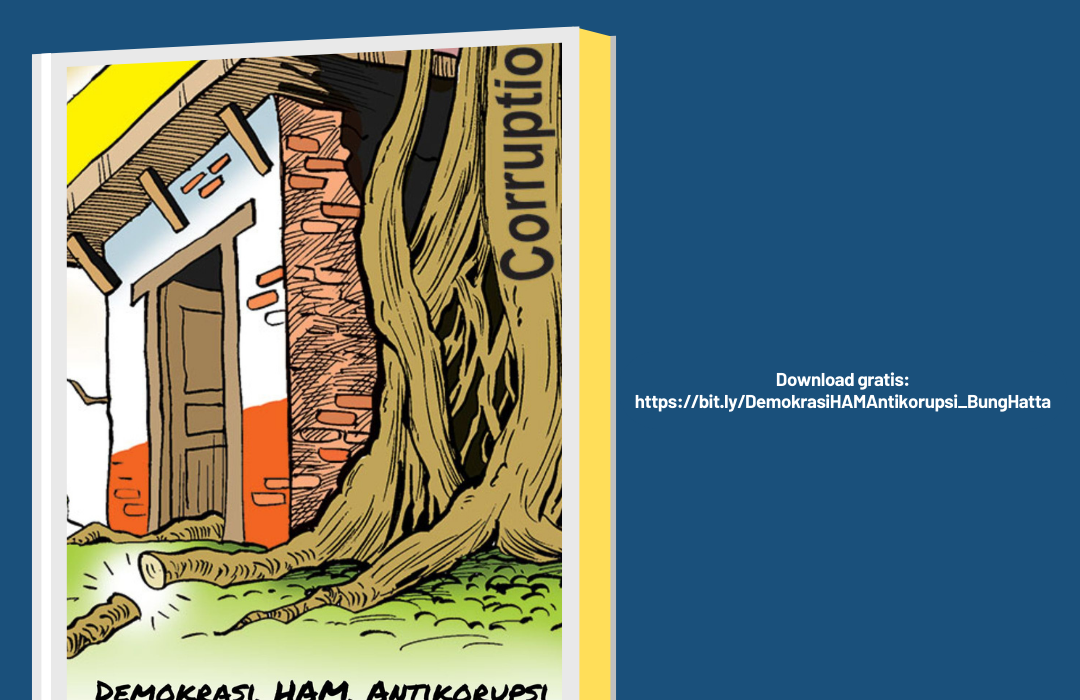





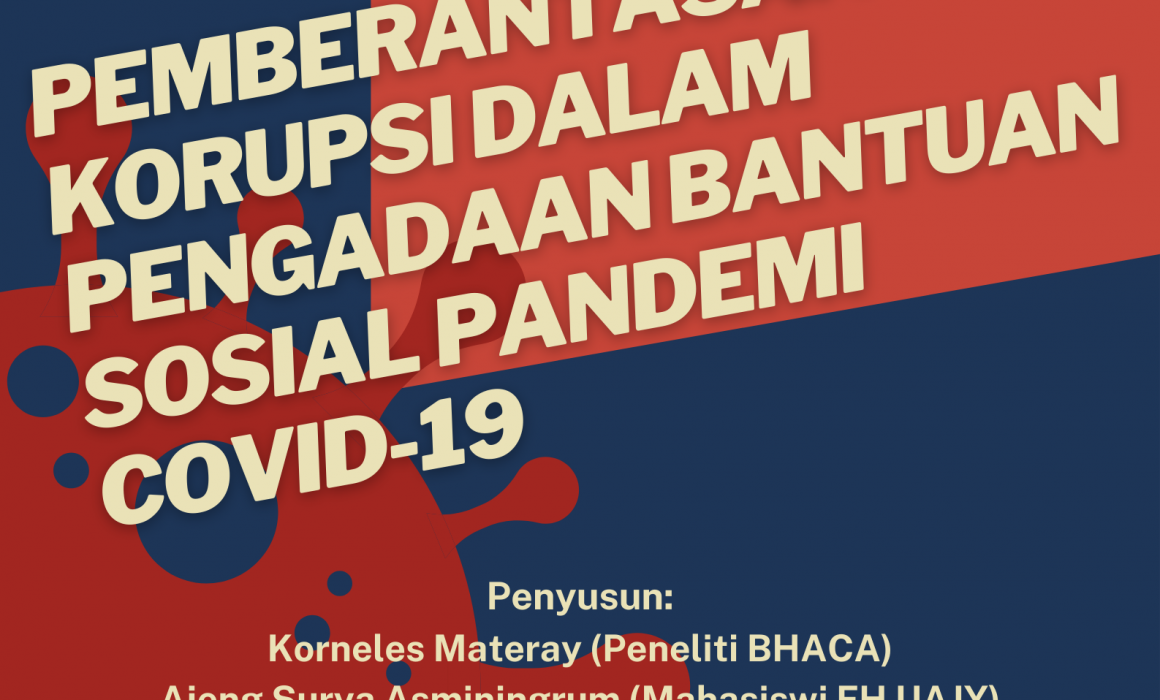
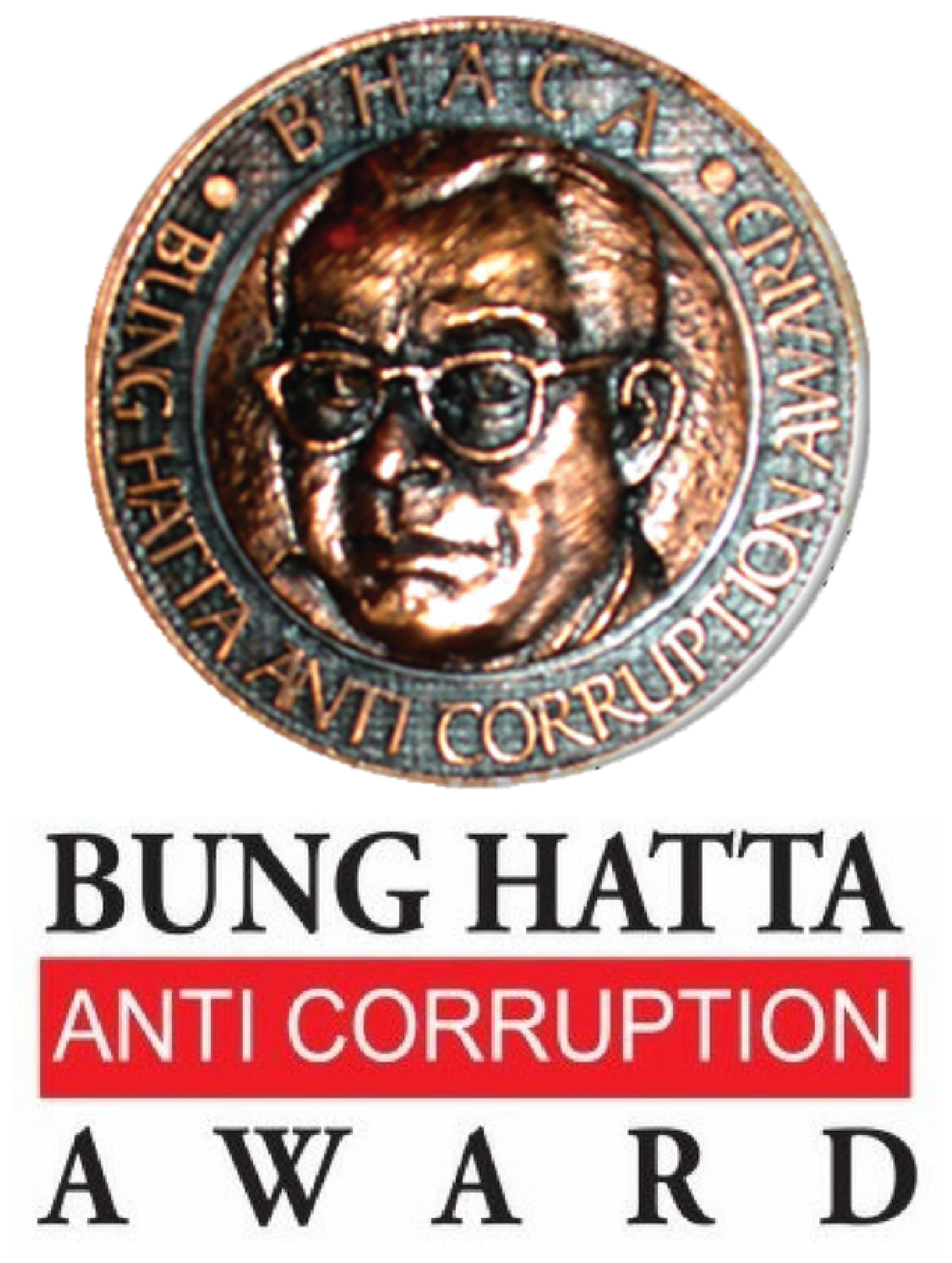
Recent Comments