Para ahli memprediksi bahwa perang melawan virus korona dapat memakan waktu yang tidak sebentar. Dengan demikian, diperlukan langkah-langkah yang strategis dan berorientasi jangka panjang tidak hanya untuk menekan laju persebaran virus korona namun juga memitigasi dampak pandemi. Bagaimana evaluasi dari langkah-langkah yang sudah dilakukan serta strategi berkelanjutan apa yang perlu dilakukan setelahnya?
Perkumpulan Bung Hatta Anti Corruption Award mengundang Herry Zudianto (Walikota Yogyakarta 2001-2011, Peraih BHACA 2010), Ita F. Nadia (Komisioner Komnas Perempuan 1999-2006, Koordinator Solidaritas Pangan Jogja), dan dr. Pandu Riono (Ahli Epidemiologi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia) dalam diskusi online berjudul, “Akuntabilitas Penanganan Pandemi Covid-19: Peran Negara dan Masyarakat” pada Kamis, 14 Mei 2020
Pada awal ditemukan kasus positif, tentu semua orang menginginkan agar virus tidak menyebar luas, apa lagi dalam waktu yang singkat. Pengujian dan pelacakan menjadi pakem yang disepakati ahli kesehatan seluruh dunia untuk menekan laju penyebaran virus dan kemudian meredam dampak sosial dan ekonomi dari pandemi. Sayangnya, menurut dr. Pandu Riono, ketidaksigapan pemerintah membuat Indonesia terlambat dalam menangani pandemi hingga tidak lagi bisa melacak persebaran virus. Fokus pemerintah untuk memitigasi dampak ekonomi dengan bersikap lunak terhadap pembatasan sosial justru dapat meningkatkan potensi kerugian ekonomi yang jauh lebih besar. Dr. Pandu melihat bahwa narasi new normal yang mulai digaungkan seharusnya berorientasi jangka panjang, yakni membudayakan 3M (menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak), pembatasan sosial, serta membangun kemandirian negara dalam memenuhi kebutuhan dasar.
Pandemi bukanlah semata-mata problem kesehatan, melainkan juga berdampak secara ekonomi dan sosial. Dampak ini juga secara timpang lebih besar dialami oleh kelompok marjinal, yakni masyarakat yang bekerja di sektor informal. Solidaritas Pangan Jogja (SPJ) memutuskan untuk membentuk dapur umum untuk menyuplai pasokan makanan kepada kelompok marjinal, terutama yang tidak terdaftar sebagai penerima bansos pemerintah karena tidak memiliki KTP maupun yang tidak memiliki rumah untuk memasak sembako. Selain kompleksitas pemetaan penerima bantuan, tantangan lain yang dialami SPJ adalah represi dari aparat penegak hukum atas nama pemberlakuan protokol jaga jarak. Atas alasan tersebut, koordinator SPJ, Ita F. Nadia, melayangkan surat kepada Presiden Joko Widodo untuk menghentikan tindakan-tindakan represif atas nama pencegahan penularan Covid-19 dan melindungi rakyat yang bergotong-royong saling membantu di situasi pandemi ini, seperti yang dilakukan oleh SPJ. Solidaritas untuk menghidupkan dapur umum dilakukan oleh berbagai elemen masyarakat, mulai dari penjual nasi kucing, peternak, mahasiswa, hingga pekerja seks.
Solidaritas antar warga inilah yang juga dinilai Herry Zudianto sebagai kunci untuk membangun resiliensi warga menghadapi bencana, terlebih hal serupa sudah pernah berhasil menggerakkan Yogyakarta bangkit dari bencana gempa dan erupsi Gunung Merapi. Yang membuat bencana pandemi lebih menantang adalah ketidakpastian berapa lama bencana ini akan berlangsung. Dengan demikian, diperlukan kebijakan yang tegas dan berorientasi jangka panjang, sebab melalui kebijakanlah nasib hidup banyak orang bergantung. Sebagai warga sipil yang pernah memiliki pengalaman mengemban kursi eksekutif lokal, Herry menilai bahwa pemerintah perlu menggunakan pendekatan dialog dengan masyarakat ketimbang represi.
Rekaman Diskusi Online BHACA bertajuk “Evaluasi & Proyeksi Keberlanjutan Penanganan Pandemi Covid-19” yang diselenggarakan pada 14 Mei 2020 dapat disaksikan di Facebook Bung Hatta Award dan YouTube Bung Hatta Award.



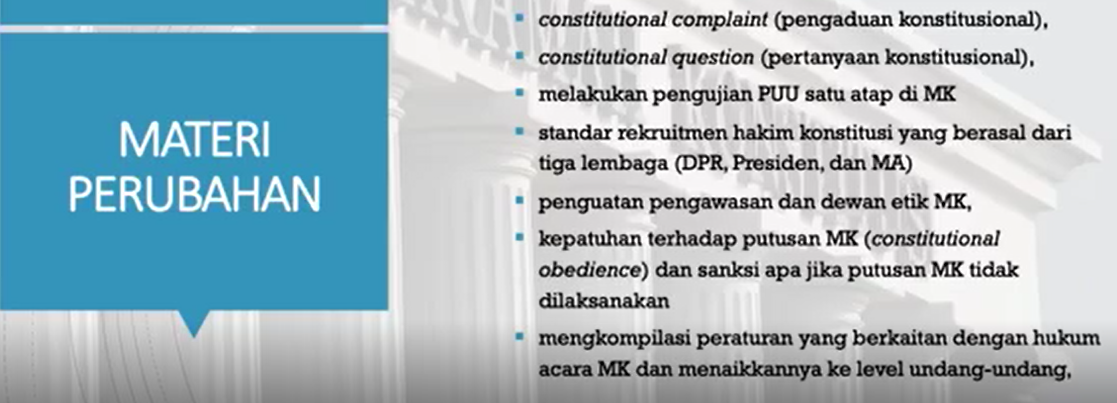





Recent Comments