Dalam implementasinya, bansos covid-19 mengalami banyak kendala seperti; data yang tidak valid, pemotongan dana bansos pungutan liar, dana bansos yang bocor ke ASN dan ibu-ibu rumah tangga yang tidak memiliki usaha, terbatasnya SDM untuk merealisasikan bansos, dan kurangnya sosialisasi kepada masyarakat. Bersamaan dengan munculnya berbagai permasalahan tersebut, korupsi bansos pun semakin menggeliat. Penyusunan policy paper ini berdasarkan observasi yang sebelumnya telah dilakukan untuk menjawab pertanyaan bagaimana pemberantasan korupsi dalam pengadaan bansos pandemi covid-19.

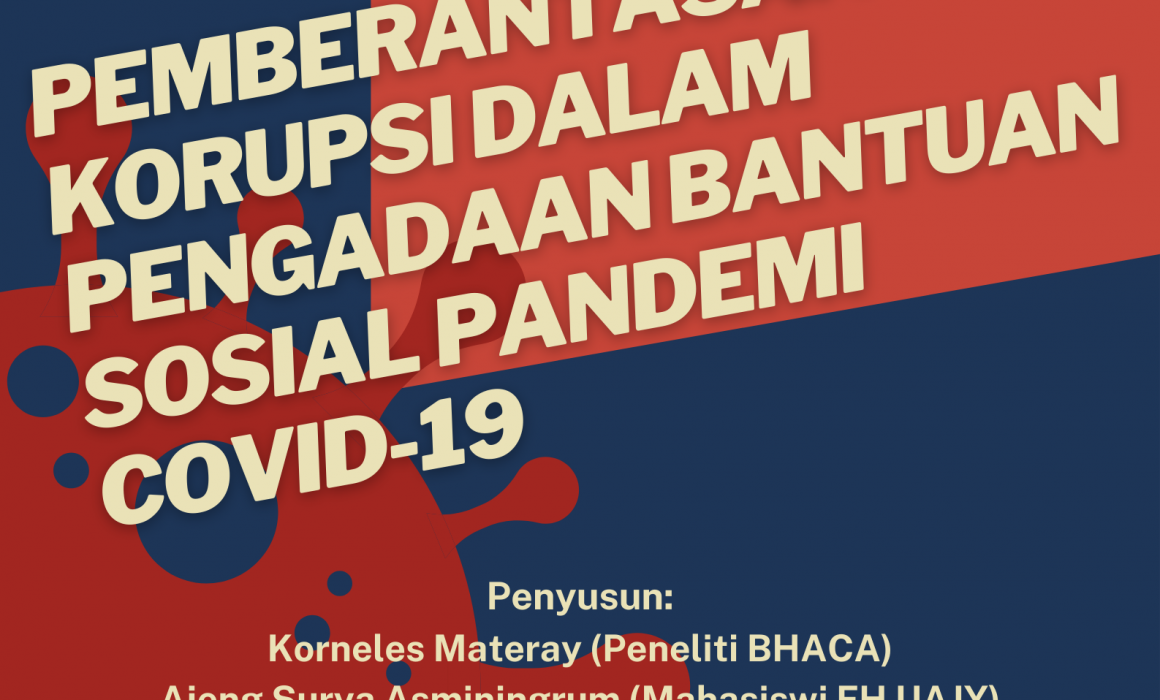










Recent Comments