Korupsi adalah gejala kompleks. Terdapat sejumlah sudut pandang untuk membedahnya. Salah satunya adalah sudut pandang psikologis, yaitu psikologi orang yang takut mati. Apakah ada manusia yang tidak takut mati? Saya akan jelaskan. Kita semua menyimpan ketakutan akan kematian, setiap hari. Ketakutan itu kita simpan diam-diam, walau sesekali kita ungkapkan juga secara terbuka.
Bagaimanapun, rasa cemas akan kematian itu menyiksa batin seseorang. Orang merasa tidak berdaya di hadapan fakta kematian. Fakta itu berpotensi membawa kehampaan atau perasaan bahwa “saya dan hubungan-hubungan saya tidak akan berlanjut”, “saya akan menjadi nihil”. Nah, supaya pikiran seseorang tidak dibalut dengan rasa cemas akan kematian, orang membangun cara hidup. Tujuannya satu, yakni untuk melindungi diri dari kecemasan akan kematian itu, bahkan bila dapat, mengatasi kematian itu. Orang ingin “mengabadikan” hidupnya. Apakah mungkin? Bagaimana caranya?
Manusia adalah makhluk yang kreatif. Ia tidak mau dibatasi oleh kematian. Oleh karena itu “keabadian” dibangunnya secara psiko-simbolik karena badan pasti hancur. Dia membangun makna hidup, dia memeluk atau menganut pandangan hidup tertentu. Dengan cara tersebut, harga diri seseorang yang tadinya jatuh di hadapan fakta kematian yang tak terhindarkan dan tidak bisa dia kendalikan itu, kemudian ditegakkan kembali.
Persis di sinilah titik kritisnya. Pandangan hidup semacam apa yang bisa sukses mengatasi perasaan diri kecil, “bodoh”, dan tak berarti di hadapan fakta kematian? Ada orang-orang yang menyerahkan dirinya pada pandangan hidup yang menekankan penguasaan terhadap lingkungan. Dengan berkuasa dia merasa diri bermakna. Kekuasaan dipandang sebagai rantai yang menghubungkan segala macam hal, orang, dan peristiwa, yang membuat dia tidak gamang lagi. Dengan itu, dia merasa—sekali lagi: merasa—bahwa dia telah menggengam sesuatu yang tidak dapat dicuri atau diambil oleh kematian. Eksistensi dirinya merasa diteguhkan.
Hasrat berkuasa itu biasanya beriringan dengan hasrat akan materi. Bila kita cermati, materialisme dan konsumtivisme telah menjadi semangat zaman ‘now’, sayangnya, sebagai cara paling dangkal dan banal yang dipilih manusia untuk memulihkan dan meningkatkan makna dan harga diri yang dirusak oleh fakta tentang ancaman kematian. Dengan uang, kekuasaan, dan kepemilikan, kebanyakan orang merasa aman bahkan bahagia secara biologis, psikologis, dan kultural. Tidak heran bahwa orang-orang seolah sedang berlomba-lomba untuk secepat mungkin meraih hal-hal tersebut, dengan berbuat korupsi, supaya kecemasan akan kematian berhenti mengejarnya. Apakah kecemasan itu benar-benar berhenti, katakanlah jika orang mencapai puncak kekuasaan dan kepemilikan; itu persoalan yang lain lagi.
Oleh kreativitasnya itu, perasaan akan keabadian juga diciptakan manusia melalui pemikiran bahwa walaupun tubuh fisik ini hancur, namun gen yang dia warisi melalui putra-putri dan cucu-cicitnya akan melambangkan bahwa keberadaan dirinya berlanjut walau dia sudah mati. Secara kultural, gen itu berkorespondensi dengan nama keluarga. Itu sebabnya korupsi itu sangat egois. Pusat sebenarnya adalah diri sendiri, tetapi seolah-olah diabdikan untuk kepentingan orang lain.
Kenyataannya, kreativitas manusia membuat perhatiannya tentang untung-rugi material menggunakan sarana yang disebut atau dianggapnya sebagai “keadilan sosial”. Dikaitkan dengan ungkapan sebelumnya, mengenai “kekuasaan sebagai rantai penghubung” untuk “mengatasi” kematian, akan sangat sulit rantai itu terbentuk dan terpelihara jika manusia tidak memperhatikan apa yang adil dan apa yang membahagiakan buat relasi-relasinya. Relasi atau hubungan itu justru penting untuk mengukuhkan identitas dan status seseorang. Oleh karenanya, membela harga diri kelompok dianggap sama pentingnya dengan membela harga diri orang per orang yang terancam oleh fakta tentang kematian. Ini menjadi pendorong “korupsi berjamaah”. Hal ini karena kelompok ikut menghadirkan kebanggaan dan kehormatan diri bagi seseorang yang bisa membuat orang tidak melulu terbalut oleh kecemasan akan kematian.
Kendati demikian, hal-hal di atas hanya segelintir dari sekian banyak pandangan hidup. Ada pandangan hidup yang jelas-jelas menilai bahwa perasaan abadi yang dihasilkan oleh materi dan kekuasaan yang dijustifikasi dengan persepsi “keadilan sosial” adalah sebuah ilusi psikologis. Kalaupun di atas disebut-sebut tentang adanya kebahagiaan, kebahagiaan itu dicurigai sebagai semu.
Ilusi itu berarti bahwa orang menghargai terhadap sesuatu yang sejatinya tidak berharga. Orang memberikan nilai tinggi akan sesuatu yang tidak setinggi itu nilainya. Sebagai contoh, orang yang menjalani gaya hidup “tampil” dengan segala fashion dan motif untuk dikagumi secara sosial (dan dengan demikian “sejenak” melupakan kematian), pada sejumlah momen dalam hidupnya akan mengirimkan sinyal kepada diri sendiri, dan mengatakan bahwa ada aspek diri yang lebih hakiki daripada sekadar impresi yang ada di permukaan itu. Diri yang ‘tampil’ itu ternyata bukan diri yang otentik, bukan diri yang sejatinya diinginkannya, dan dia harus membayar dengan memburuknya pandangan terhadap moralnya sendiri.
Terhadap sinyal itu, orang dapat berulang-ulang menyerahkan dirinya pada sesuatu yang dianggap sebagai “tekanan” semangat zaman yang tak terhindarkan. Dengan demikian, korupsi pun dibenarkan, bahkan diberikan kerangka makna sesukanya sendiri, misalnya “korupsi itu pelicin pembangunan dan untuk kepentingan kita yang lebih besar”. Sampai pada taraf psikologis ekstrim, emosi moral—yaitu rasa malu dan rasa bersalah—yang seharusnya fungsional untuk mengantisipasikan dan mengerem perilaku koruptif menjadi kendur dan mengalami erosi. Orang bahkan tidak segan untuk melakukan apa yang dalam masyarakat kita digambarkan sebagai “maling teriak (orang lain) maling” atau mengorbankan orang lain demi citra dirinya yang dibangun dengan mental korup.
Oleh karena itu, dinamika “psikologi orang yang takut mati” ini mesti dipahami dan diberikan implikasi sosial kalau kita ingin mencegah dan memberantas korupsi. Bukan dengan serta-merta menganjurkan dan menerapkan hukuman mati, apalagi jika kita belum mampu menjamin juga bahwa sistem hukum kita sudah bebas dari korupsi. Sekarang memang ada gejala yang namanya anti-intelektualisme, sederhananya: kemalasan berpikir, sehingga solusi-solusi yang bersifat simplistik, seperti hukuman mati, pun ditelurkan.
Saya mengajak kita semua untuk memeriksa pandangan-pandangan hidup apakah yang bekerja dalam diri dan masyarakat kita yang berguna untuk mengatasi kecemasan akan kematian. Kematian ternyata secara paradoksikal merupakan etos pertumbuhan karakter hidup seseorang, apakah ke arah yang lebih baik atau lebih buruk. Tetapi, pandangan-pandangan itu perlu disadari saling berkompetisi dan menciptakan apa yang oleh sosiolog disebut situasi anomik atau kesimpangsiuran norma. Mana sajakah yang berpotensi membungkam, atau sebaliknya, memfasilitasi moralitas positif? Persepsi tentang keadilan sosial seperti yang dipaparkan sebelumnya perlu dipikirkan ulang.
Wajib juga jujur dengan bahasa kita sendiri. Kalau pelicin sejatinya adalah pemorakporanda, apakah akan bertahan dengan sebutan pelicin? Contoh lain, dalam dunia Perguruan Tinggi (yang kata orang, disanalah “nurani masyarakat” terletak), praktik “bagi-bagi nama” (gift authorship) dalam penulisan artikel jurnal ilmiah tidak sedikit terjadi. Seorang guru/dosen yang disebut “pembimbing” namun tidak signifikan menyumbangkan gagasan maupun tulisan atas karya ilmiah bimbingannya tetapi menghasut siswa/mahasiswanya untuk mencantumkan namanya sebagai salah seorang penulis artikel jurnal/prosiding konferensi demi untuk memperoleh angka kredit kenaikan jabatan. Demikian juga terjadi di antara sesama sejawat dan hubungan atasan-bawahan di kampus. Bukankah ini wajah korupsi akademik yang dipoles dengan bahasa “gotong royong”, “kolaborasi”, dan “supervisi”? Apakah istilah “rasuah” yang digunakan oleh media massa mengecilkan pemahaman kita tentang “korupsi”?
Selanjutnya, mana yang bernilai dan mana yang tidak bermakna bagi kemanusiaan kita perlu dirumuskan sungguh-sungguh. Saya dengar, sedang direncanakan perumusan 25 butir Pancasila oleh Unit Kerja Presiden. Ini merupakan inisiasi yang bagus. Hanya saja problem “verbalisme Pancasila” selama ini perlu melibatkan studi-studi yang kreatif, supaya anti-intelektualisme tidak terjadi. Ada perbedaan yang jelas antara “kepatuhan (di mata) publik” (public compliance) dan “penerimaan batin” (private acceptance). Kalau suatu saat lahir “Indeks Keber-Pancasila-an”, apakah perbedaan tersebut telah diperhitungkan, supaya jangan sampai terjadi korupsi dalam makna dan pengamatan? Jawab atas pertanyaan-pertanyaan ini diharapkan mendekatkan kita pada pencegahan dan pemberantasan korupsi.
Akhirnya, sama halnya bahwa pengatasan terhadap tendensi korup seseorang dimediasikan secara jelas oleh pandangan hidup dan bahasa, maka pencegahan dan pemberantasan kecenderungan korup secara sosial/institusional seharusnya dimediasikan secara tegas oleh perangkat sosial/institusional yang secara sengaja diciptakan untuk itu. Penguatan Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi sentral dalam hal ini.
Juneman Abraham, Pakar Psikologi Sosial
Tulisan ini pertama kali terbit di Bernas.id dengan judul “Korupsi Dipandang dari Sisi Psikologi Sosial” edisi 22 November 2017

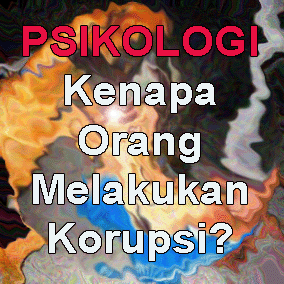









Recent Comments